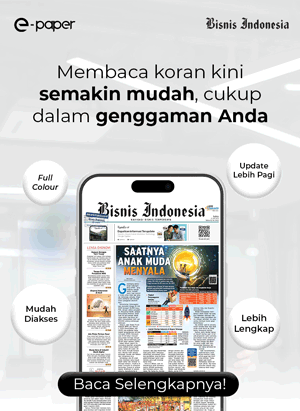Bisnis.com, MALANG — Produksi ikan tangkap lemuru di Muncar, Kabupaten Banyuwangi terus menurun menjadi 29.000 ton pada 2024 yang dipicu pola penangkapan yang berlebihan dan tidak selektif.
Profesor dalam bidang Ilmu Dinamika Populasi Ikan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya, Prof. Daduk Setyohadi, mengatakan ikan lemuru Selat Bali ialah satu-satunya perwakilan perikanan spesies tunggal di Indonesia dengan Alat Penangkapan Ikan (API) spesifik purse seine.
Sejak tahun 2010, tren penangkapan ikan lemuru menunjukkan penurunan tajam tanpa adanya pemulihan signifikan.
"Penurunan ini utamanya disebabkan oleh pola penangkapan yang berlebihan dan tidak selektif, sebagian besar ikan termasuk yang belum dewasa, ikut tertangkap sebelum sempat berkembang biak. Sebelum 2010, hasil ikan tangkap lemuru mencapai 40.000 ton/tahun," kata Daduk Setyohadi di sela-sela pengukuhan sebagai guru besar di UB, Rabu (28/5/2025).
Melihat ancaman ini, dia mengembangkan pendekatan baru yakni Teknologi Sertifikasi Perikanan Lemuru Berkelanjutan Selat Bali (TSPLB-UB).
Ini adalah sistem sertifikasi lokal yang dirancang agar lebih sederhana, terukur, dan cocok untuk kondisi Indonesia tanpa harus menunggu rumitnya standar sertifikasi internasional.
Baca Juga
Teknologi sertifikasi ini memerlukan informasi 6 indikator utama, namun sangat fokus pada kepastian terhadap tingkat keberlanjutan sumber daya yang akan disertifikasi.
Dengan demikian proses sertifikasi bisa dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan standar sertifikasi global lainnya.
Berbekal kondisi data perikanan Indonesia yang tersedia saat ini, teknologi sertifikasi TSPLB-UB sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan diaplikasikan pada perikanan tangkap di Indonesia.
Teknologi ini bisa digunakan selanjutnya oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam menyusun kerangka operasional sertifikasi perikanan tangkap.
Dia menegaskan, ada 6 indikator TSPLB-UB, yakni rasio potensi pemijahan ≥ 30%, jumlah tangkapan ≤ 70% dari potensi lestari, ikan tertangkap 3,81 cm, kepatuhan izin usaha ≥ 99%, dan kepatuhan pelaporan logbook ≥ 99%.
"Usulan ini lebih sederhana, hanya menggunakan 6 indikator, terukur dan transparan karena berbasis data lapangan, dan kotekstual karena disesuaikan dengan karekteristik perikanan Indonesia," kata dia.
Profesor bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Perikanan Tangkap di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UB, Prof. Gatut Bintoro, yang juga dikukuhkan pada kesempatan yang sama, mengusulkan model manajemen sumber daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan Berbasis Ramah Ekologi, Ekonomi dan Sosial (PREES) UB.
Menurutnya, PREES-UB hadir sebagai jawaban atas krisis sumber daya perikanan yang ditandai dengan overfishing, praktik IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing, dan degradasi habitat laut akibat perubahan iklim.
"Pengelolaan yang baik tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya," kata Gatut Bintoro dalam orasinya.
Model ini dirancang dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan 3 pilar utama yakni konservasi ekosistem laut (ekologi), peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (ekonomi), dan keterlibatan aktif komunitas lokal (sosial).
"Keberhasilan pengelolaan perikanan dalam model ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat pesisir," ujarnya menekankan pentingnya peran masyarakat lokal.
Model ini disampaikan juga menekankan perlunya penguatan teknologi informasi seperti digitalisasi pemantauan stok ikan dan sistem informasi spasial.
Teknologi ini mendukung transparansi, akurasi data, serta efektivitas kebijakan pengelolaan di wilayah pesisir.
Pada aspek ekologi, Prof Gatut menekankan pentingnya Zona Perlindungan Laut (Marine Protected Areas/MPAs), pengaturan waktu penangkapan dan alat tangkap ramah lingkungan. Pendekatan-pendakatan ini diambil karena mengutakan aspek keberlanjutan.
Meskipun menawarkan solusi holistik, kata dia, model ini diakui memiliki tantangan besar, khususnya dalam hal koordinasi lintas sektor antara pemerintah, ilmuwan, nelayan, dan pemangku kepentingan industri.
Keterbatasan data ilmiah, infrastruktur, dan resistensi terhadap regulasi juga disebut sebagai hambatan implementatif.